Tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri (Heraklitus)
Mungkin ini juga yang mendasari semangat pemberontakan epistemologi pada abad ke-17 terhadap gereja yang kemudian menghasilkan manusia-manusia modern yang otonom. Tetapi akibat dari itu, ternyata menghasilkan krisis kompleks yang multidimensional bahkan menjadi derita peradaban yang jauh lebih besar dari sebelumnya.
Krisis ekologis, kekerasan, dehumanisasi, moral, kriminalitas, kesenjangamn sosial yang kian menganga, dan ancaman kelaparan serta berbagai penyakit lain merupakan akibat dari apa yang dibahasakan Husein Nasr sebagai cerminan dari keterpilahan, konflik dan ketersingan dalam diri bathin masing-masing penghuni dunia. Jika kita merunut sebab krisis global diatas, menurut Fritjof Capra dapat dilacak dari cara pandang dunia (world view) manusia modern. Pandangan dunia yang diterapkan selama ini yaitu pandangan dunia mekanistik-linier Cartesian-Newtonian.
Cara pandang demikian mengakibatkan manusia modern mengalami alienasi. Dalam pandangan Fromm, alienasi adalah penyakit mental yang ditandai perasingan keterasingan dari segala sesuatu; sesama manusia, alam, Tuhan dan jati dirinya. Bahkan perilaku konsumerisme, hedonisme dan gebyar globalisasi lainnya merupakan bentuk pelarian manusia modern dari alienasi.
Setidaknya ada tiga kecendrungan manusia modern yang mengalami situasi keterasingan atau alienasi. Pertama, mereka yang teralienasi dari Tuhannya, yang disebabkan terutama oleh prestasi sains dan teknologi, sehingga menjadi positivis. Kedua, mereka yang teralienasi dengan lingkungan sosialnya, yang oleh Alfin Tofler diistilahkan dengan future shock. Ketiga, mereka yang teralienasi dari Tuhannya sekaligus lingkungan sosialnya. Kondisi diatas, akibat dari tercerabutnya sisi kedalaman bathin manusia yang berupa roh atau spiritualitas. Seperti yang disinyalir Peter Berger, “bahwa manusia modern telah meninggalkan nilai-nilai supranatural”. Pandangan dualisme bahwa roh dan jasad adalah terpisah menyebabkan manusia terjerembab dalam kehancuran eksistensinya. Bahkan pandangan ini adalah salah satu akar persoalan utama yang mengkarakterisasi pelbagai problem dan krisis global peradaban modern. Akibat lebih jauh adalah hilangnya orientasi hidup yang penuh kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang sesama manusia. Yang terjadi adalah sebaliknya, keresahan, ketakutan dan kondisi kejiwaan lainnya.
Mungkin secara materi sangat kaya, segala keperluan hidupnya sudah terpenuhi semua, tetapi ada kesadaran eksistensial yang ada pada diri manusia yang harus dipupuk untuk keseimbangan hidup, dan ini yang tidak ada malah dinegasikan dalam diri manusia modern yang sering dikatakan sebagai the post industrial society, suatu masyarakat yang telah mencapai tingkat kemakmuran materi sedemikian rupa dengan perangkat teknologi yang serba otomatis dan mekanis, bukannya mendekati pada kebahagiaan hidup, melainkan sebaliknya, kian dihinggapi rasa cemas. Sehingga tanpa disadarinya integritas kemanusiaannya tereduksi lalu terperangkap pada sistem rasionalitas teknologi yang sangat tidak manusiawi. Bahkan Nasr menyatakan lebih jauh, masyarakat modern sedang berada diwilayah pinggiran eksistensinya sendiri, bergerak menjauh dari pusat, baik menyangkut dirinya sendiri maupun dalam lingkungan kosmosnya.
Untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia modern dan yang diakibatkannya, telah banyak pemikir-filosof memberikan tawaran perspektif untuk mengatasi problem tersebut. Misalnya, E.F Schumacher menyarankan pemulihannya harus datang dari dalam diri sendiri. Husein Nasr menyarankan untuk kembali pada dimensi bathin atau spiritual manusia.
Spiritualitas; sebuah perspektif
Spiritualitas disini bukan suatu keberadaan diri yang biasanya dicapai lewwat riyadhah atau rangkaian disiplin ritual tertentu untuk mencapai ‘Sang Realitas’ yang tak dapat dilihat dalam pengalaman biasa. Pemahaman spiritualitas seperti ini tidak salah, karena memang mempunyai pendasaran dalam semua agama. Tetapi dengan pemahaman seperti itu nampak bahwa spiritualitas hanya sekedar laku bagi seorang untuk mencapai realitas tertinggi tanpa punya implikasi sosial didalamnya.
Spiritualitas dimaksud adalah sebagai basis setiap aksi kebudayan yang kita lakukan. Pencapaian spiritualitas tingkat tinggi harus memanifestasi dalam laku kebudayaannya sehari-hari. Bagi pedagang, petani, politisi, ilmuwan, ekonom dan peran-peran lainnya harus mencerminkan dari spiritualitasnya. Dalam artian, segala aktivitas yang dilakukannya harus diarahkan pada titik pusat. Suhrawradi al-Maqtul menyebut dengan cahaya diatas cahaya (nur ’ala nur). Jika yang terjadi sebaliknya berarti masih ada split dalam dirinya dalam melihat realitas. Karena spiritualitas melibatkan komitmen pada Tuhan dan manusia, keduanya menjadi kesadaran tunggal dalam diri manusia.
Seperti Muhammad, ketika beliau sampai pada puncak spiritualitas, naik kelangit tertinggi bukannya malah berpaling dari tanggung jawab kemanusiaannya, melainkan terjalin hubungan antara kehendak suci dilangit dengan orientasi manusia di bumi. Dengan kata lain spektrum Ilahi dengan spektrum kemanusiaan disisi lain secara metafisis tidak diletakkan dalam ruang yang kita pahami dalam hidup keseharian. Tetapi keduanya menyatu dalam kesadaran, sehingga bagi seorang yang sampai pada tingkatan spiritualitas tertentu, perilaku kemanusiaannya merupakan cerminan dari kualitas Ilahiah.
Kalau kita kembalikan kepada posisi manusia di bumi yaitu sebagai khalifah Tuhan atau mendataris-Nya, maka keagungan kita tidak akan bisa terpahami tanpa keterkaitan dengan Tuhan. Bila ridho Tuhan tidak menjadi pusat orientasi kita dalam menjalani kehidupan ini, maka kualitas hidup kita akan menjadi rendah. Dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan akhir, kita akan terbebaskan dari derita alienasi, karena Tuhan adalah pesona yang maha hadir dan maha mutlak. Eksistensi yang relatif akan lenyap kedalam eksistensi yang absolut. Kesadaran akan kemahahadiran Tuhan akan membuat kita selalu memiliki kekuatan, pengendalian dan sekaligus kedamaian, sehingga kita merasa dalam orbit Tuhan, tidak dalam orbit dunia yang tidak jelas juntrungnya.
Sebagai visi baru dalam kehidupan, sebenarnya spiritualitas merupakan perjalanan kedalam diri manusia sendiri. Bisa jadi seorang pedagang, polisi, ilmuwan, ekonom, dan lainnya mampu mencapai apa yang diinginkannya, namun amat mungkin ia miskin dalam mengenal eksistensi dirinya (lihat fenomena manusia modern). Mungkin ia gagal memahami makna hidup ini, kemana perjalanan dan untuk apa diciptakan. Sehingga apa yang dihasilkan dengan seluruh daya dan upaya tidak bisa memberikan kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian.
Mengenal eksistensi diri adalah keniscayaan untuk membangun kepedulian dan kecintaan terhadap kemanusiaan. Jika ini gagal dilakukan, maka mengenal orang lain juga gagal. Menarik ajaran klasik yang mengatakan, bahwa kita hanya dapat memahami orang lain (sisi kemanusiaan), jika kita mengenal diri kita. Bahkan kaitan dengan Tuhan pun, sabda Nabi “siapa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya”. Jadi pemahaman mengenai yang lain bergantung pemahaman mengenai diri kita sendiri. Tanpa kerja bathin ini atau berhubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi yang tidak dapat dimanipulasi sebagai basis aksi kebudayaan, maka kehidupan manusia akan penuh dengan pengobjekan orang lain, manipulasi, penindasan dan kekejaman yang muncul bukan saja hanya karena kita tidak mengenal bathin orang, tetapi justru kita tidak mengenal diri sendiri.
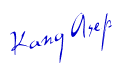
Sabtu, 30 Januari 2010
Kembali ke Akar Kembali ke Sumber
 Categories : Dari A Tom
Categories : Dari A Tom Sabtu, Januari 30, 2010
Sabtu, Januari 30, 2010
 M Teguh A Suandi
M Teguh A Suandi


1 comments:
like
Posting Komentar